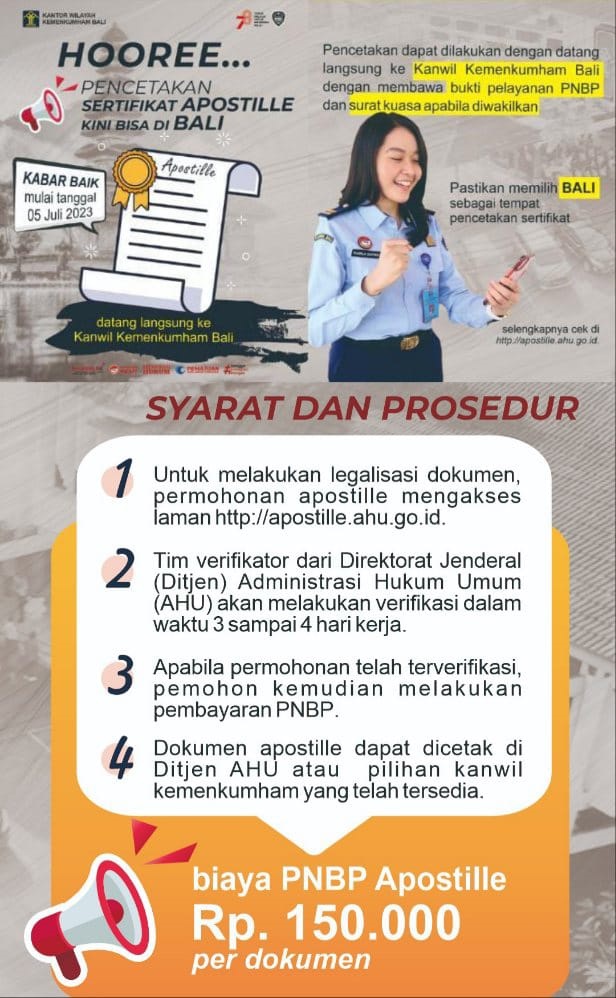Gempita.co – Izin berkampanye pemilu di institusi pendidikan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini menuai pro kontra.
Padahal, ini bukan isu baru, kata Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati. Isu ini selalu muncul dari pemilu ke pemilu.
Dia menilai, sebaiknya kampanye dilakukan mulai tingkat SMU untuk siswa mulai kelas 11 atau kelas 2 SMA, tetapi tidak pada tingkat di bawah itu.
Itu pun, Neni mengingatkan, “Bagaimana SOP (standard operational procedure) dan lain-lainnya, KPU harus mengatur secara detail berkaitan dengan hal itu.”
Sementara Ikatan Guru Indonesia (IGI) dengan keanggotaan yang luas juga membahas izin MK ini. Mereka menyimpulkan bahwa efek berkampanye di sekolah akan sangat negatif. Kekhawatiran pada anak didik, terutama yang belum mempunyai hak pilih, membuat mereka berketetapan bahwa sekolah perlu dilindungi dari politik praktis. Bagi yang sudah punya hak pilih, kata ketua IGI Danang Hidayatullah, kampanye bisa dilakukan tetapi tidak di sekolah.
“Logika saya sederhana saja. Ada berapa banyak calon legislatif yang akan berebut masuk ke sekolah-sekolah. Itu saja sudah sangat rawan. Yang kedua, kalau pun masuk, itu membahayakan. Akan terbangun relasi kuasa,” ujar Danang.
Neni, penulis buku ‘Jalan Berliku Demokrasi Indonesia’, setuju, kampanye di sekolah memang rentan. Apalagi, dinamika pemilu sangat cepat dan sarat akan kepentingan.
“Sekolah berpotensi terseret ke lingkaran politik praktis dan tidak bisa memegang sikap netral. Ini yang menurut saya, it’s very dangerous,” tukasnya.
Danang menegaskan, IGI tidak menutup demokrasi di sekolah. Tetapi, ia percaya, masyarakat belum siap bila kampanye digelar di sekolah.
“Di sekolah itu, kan multikultur ya. Terbuka, terus juga beda suku, agama, termasuk beda pilihan politik. Kalau tiba-tiba sekolah itu menjadi tempat kampanye, bisa saja terjadi, bisa diplot oleh satu dua partai atau mungkin caleg-caleg tertentu yang punya pesan tersendiri ke pihak sekolah: ‘Ini kalau bisa jangan ada yang masuk selain saya,’ misalnya. Itu bisa dan sangat mungkin terjadi,” kata Danang.
Di luar itu, kata Danang, sekolah berisiko dicap berafiliasi dengan partai tertentu kalau kebetulan hanya partai itu yang datang dan tidak tersentuh partai lain. Imbasnya, ketika penerimaan murid baru, orang tua akan ingat bahwa sekolah ini pendukung calon tertentu atau beralifiasi dengan partai tertentu.
Faktanya, kata Neni, ketika berkampanye, calon atau partai umumnya akan memberikan sesuatu, mulai dari stiker sampai uang.
“Ya, kalau misalnya caleg enggak bisa bawa apa-apa, kandidat enggak bawa duit, enggak bisa memberikan sesuatu yang bisa dinikmati oleh masyarakat pada hari itu, itu akan dianggap ya kere-lah, enggak bisa bawa apa-apalah. Kemudian, ngapain? Memangnya kita mau makan program? Memangnya kita mau makan politik gagasan? Kan istilahnya seperti itu. Politik gagasan itu enggak laku dalam masyarakat kita,” tandasnya.
Berdasarkan hasil penelitian DEEP Indonesia, Neni mengatakan, pemilih Indonesia sudah masuk kategori moral hazard pemilih.
“Tahu politik uang enggak boleh. Tahu politik uang, salah. Lalu, mengambil materi dari pasangan calon yang ketika dikonversi nilainya, dalam pemilu 2024, 100 ribu (rupiah) juga sudah masuk kategori politik uang, tetapi mereka masih mau terima. Nah, saya khawatir ini justru akan mengganggu ketenteraman ketika itu terjadi di sekolah,” tambahnya.
Sumber: voa